Pelatihan Bridge CRPD: Pendalaman Materi Pengakuan dan Persamaan Hukum Dimata Penyandang Disabilitas
Sempat tertunda satu minggu, pelatihan Bridge CRPD dengan tema “Meningkatkan Kapasitas Organisasi Perempuan Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Daerah Dalam Memajukan dan Melindungi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas”, akhirnya dilaksanakan pada 13 s.d 17 Juli 2020 yang digagas oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)dengan dukungan Ford Foundatondan Direktorat JenderalBina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Selama 5 hari kegiatan pelatihan melibatkan peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tingkat provinsi se-Indonesia, serta Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) se-Indonesia. Selama kegiatan melibatkan 5 fasilitatir, salah satunya Yeni Rossa Damayanti yang diminta memberikan pemahaman atau pendalaman Pasal 12 Kovenan CRPD terkait Pengakuan dan Persamaan di Muka Hukum, yang dilaksanakan pada hari ke-3.
Dalam kata sambutan pembukaan pelatihan, Maulani Rotinsulu, ketua HWDI menyampaikan bahwa 4 tahun Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016tentang Penyandang Disabilitas disahkan, sudah ada 4 aturan turunan, yaitu:
1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kartu Penyandang Disabilitas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
“Kami melihat ada animo Pemerintah daerah menerbitkan Perda (Peraturan Daerah-peny) tentang Penyandang Disabilitas. Saat ini kurang lebih ada 34 Perda dari tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota”, tukas Maulani
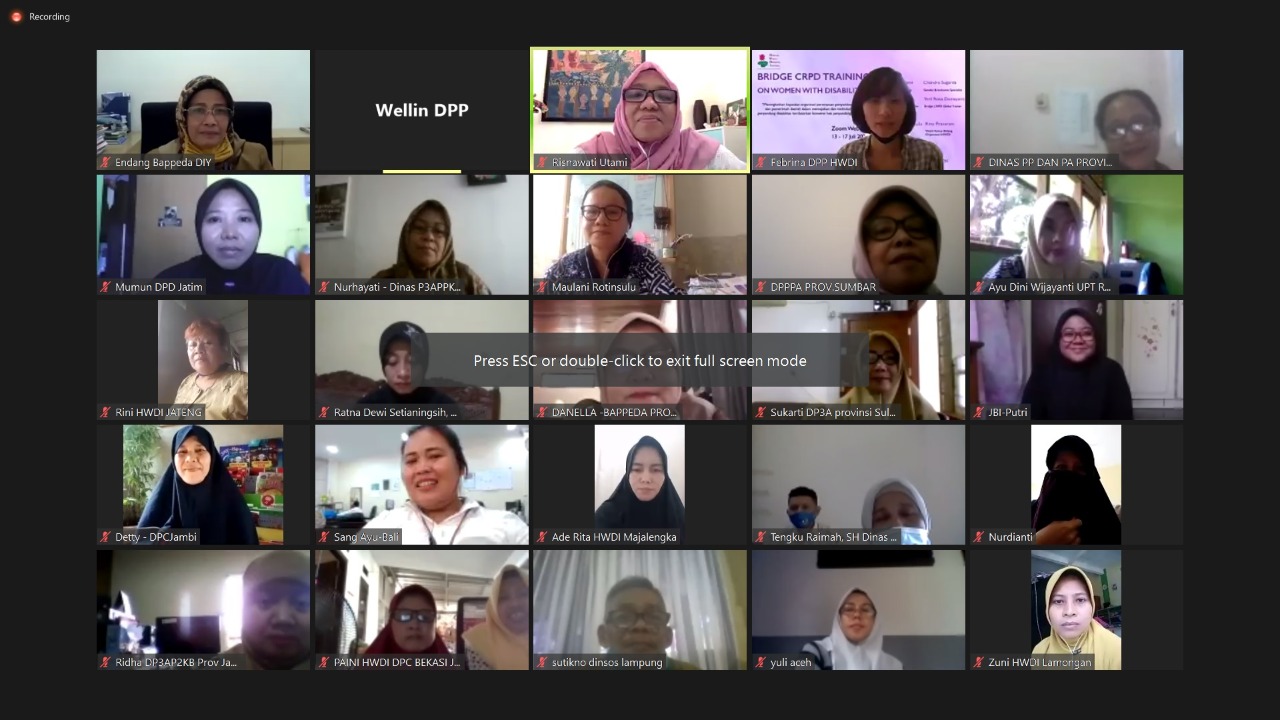 Ester M. Parafat perwakilan dari Ford Foundation, dalam sambutannya menyatakan bahwa pelaksanaan pelatihan bridge CRPD merupakan kontribusi dari hibah ford foundation untuk kelompok minoritas, khususnya penyandang disabiliutas. Pada awal tahun 2020 Ford Foundation memberikan hibah ke HWDI untuk meningkatkan kapasitas anggota HWDI dan pemerintah untuk perlindungan penyandang disabilitas sebagai bagian dari tujuan lembaga.
Ester M. Parafat perwakilan dari Ford Foundation, dalam sambutannya menyatakan bahwa pelaksanaan pelatihan bridge CRPD merupakan kontribusi dari hibah ford foundation untuk kelompok minoritas, khususnya penyandang disabiliutas. Pada awal tahun 2020 Ford Foundation memberikan hibah ke HWDI untuk meningkatkan kapasitas anggota HWDI dan pemerintah untuk perlindungan penyandang disabilitas sebagai bagian dari tujuan lembaga.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah.Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni menyampaikan paparan terkait Pengurus Utamaan Isu Penyandang Disabilitas Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Ketika bicara isu disabilitas, terkadang penyandang disabilitas dikesampingkan dalam rencana penganggaran APBD. Penanganan disabilitas merupakan bagian dari layanan dasar di bidang sosial, yang kemudian seharusnya menjadi prioritas daerah dalam penganggaran. Pertanyaan kenapa tidak diurus secara maksimal?
“Dari APBD minimal sudah dipesan 20% untuk pendidikan, kemudian kesehatan 10%, infrastruktur sudah dialkokasikan 35%. belanja pegawai 37 s.d 42%. Nah dalam kondisi Covid-19 didorong ada realokasi ke bidang kesehatan. Ketika bicara penanganan penyandang disabilitas, harus dibicarakan kembali saat ini. Semuanya kembali ke pemerintah daerah.” tutur Hari Nur Cahya Murni.
Dana dari APBD untuk layanan dasar ini memang sudah ada namun sudah diplot-plot persentasenya. Tanggal 9 Desember 2020 akan dilakukan Pilkada serentak untuk memilih sekitar 270 kepala daerah atau 50% dari pimpinan daerah di Indonesia, dan enam bulan kemudian akan ada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari pemimpin terpilih, ini kesempatan HWDI mengawal isu disabilitas agar masuk dalam RPJMD, tutur Hari Nur Cahya Murni.
Kemudian paparan berikutnya disampaikan oleh Nyimas Aliah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) itu memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. Di KPPA dan P2TP2A ada bagian khusus terkait perempuan disabilitas dan anak disabilitas. P2TP2A kemudian akan diupayakan untuk dibuat UPTD. Pembentukannya didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 Perempuan disabilitas berpotensi mengalami dsikriminasi ganda karena perempuan dan disabilitas. Perempuan itu dianggap second class. Sehingga keadilan bagi mereka sangat rendah. Mereka memiliki hak yang sama dan mendapatkan jaminan sosial, serta pemberdayaan di masyarakat. Kesukesan perempuan disabilitas itu didasarkan pada kemandirian. Perempuan yang amndiri dan berperan aktif dan membantu pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Peraturan Daerah, Pemerintah daerah perlu memperhatikan isu perempuan dan anak disabilitas.
Perempuan disabilitas berpotensi mengalami dsikriminasi ganda karena perempuan dan disabilitas. Perempuan itu dianggap second class. Sehingga keadilan bagi mereka sangat rendah. Mereka memiliki hak yang sama dan mendapatkan jaminan sosial, serta pemberdayaan di masyarakat. Kesukesan perempuan disabilitas itu didasarkan pada kemandirian. Perempuan yang amndiri dan berperan aktif dan membantu pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Peraturan Daerah, Pemerintah daerah perlu memperhatikan isu perempuan dan anak disabilitas.
Pembicara berikutnya di hari ke-1 ini adalah, Eva Rahmi Kasim, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial, memaparkan pendataan penyandang disabilitas. Pasal 117 UU 8/2016 memandatkan Pemerintah memiliki data nasional penyanndang disabilitas dalan perencanaan kebijakan dan program. Pendataan menjadi mandatori turunan PP 70/2019, dimana dalam perencanaan induk disabilitas periode 2020 s.d 2035 mengamanatkan kepada Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik bekerja sama dalam sinkronisasi data, salah satunya dalam pelaksanaan Sensus Penduduk terhadap penyandang disabilitas, yang akan dilakukan pada tahun 2021. “Kami akui pendataan selama ini itu terpisah-pisah dengan konsep yang berbeda antar kementerian atau lembaga negara. Belum sinkronnya data yang ada berdampak seperti kejadian pemberian bantuan yang diberikan pemerintah saat terjadi dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu perlu ada data yang sama agar program dan kebijakan searah”, tukas Eva Rahmi Kasim.
Dia pun menambahkan bahwa pendataan identitas penyandang disabilitas berproses dengan muara akhir terkait adanya Kartu Penyandang Disabilitas sebagai benefit dari perlindungan sosial. Dengan adanya Kartu penyandang disabilitas ini pemerintah bisa me-record bantuan atau program sosial yang sudah didapat dan harus disertakan kepada penyandang disabilitas tersebut berdasarkan assessment dari program dan bantuan yang diperoleh oleh mereka. Untuk memperoleh Kartu Penyandnag Disabilitas, maka mereka harus memiliki Nomer Induk Kependudukan. Sistem pendataan kependudukan di Indonesia itu sub report, harus melaporkan ke instansi dinas sosial di daerah sehingga tidak bisa otomatis penyandang disabilitas yang punya KTP akan masuk dalam Kartu Penyandnag Disabilitas, tutur Eva Rahmi Kasim.
Setelah pemaparan tiga orang pembicara dari Pemerintah. Risnawati Utami, fasilitator pertama yang diminta memaparkan prinsip-prinsip dan implementasi dalam CRPD dengan pendekatan kembar, yaitu mainstreaming dan pendekatan spesifik penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus ikut serta dalam partisipasi yang diadopsi dan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam hal ini  Bappeda dalam RPJMD dan rencana aksi daerah dalam SDGs. Isu disabilitas ini bukan semata urusan Dinas Sosial, namun mencakup multi sector sehingga melibatkan OPD lain di daerah dalam perencanaan program, kebijakan, dan anggaran.
Bappeda dalam RPJMD dan rencana aksi daerah dalam SDGs. Isu disabilitas ini bukan semata urusan Dinas Sosial, namun mencakup multi sector sehingga melibatkan OPD lain di daerah dalam perencanaan program, kebijakan, dan anggaran.
Hari ke-2 sesi pagi Risnawati Utami melanjutkan pembahasan dengan menghubungkan konsep CRPD dengan CRDAW yang berhubungan dengan perlindungan wanita, sementara CRPD lebih kepada wanita disabilitas atau langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan eksploitasi kekerasan terhadap perempuan disabilitas. Pemerintah punya kewajiban langkah-langkah pemenuhan perenmpuan disabilitas berdasarkan usia dan ragam disabilitas
Selain itu, para peserta juga belajar konsep aksesibilitas dan akomodasi yang layak terhadap Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas wajib dipenuhi jika tidak bisa difasilitasi maka harus diberikan akomodasi yang layak. Jadi aksesibilotas itu sesutu yang bersifat permanen dan waktunya lama. Misalnya ada seorang penyandang disabilitas daksa ingin melaporkan kasusnya ke kantor polisi, kebetulan layanan pengaduan ada di lantai 2 yang tidak ada lif hanya ada tangga. Gedung itu adalah aksesibilitas. Ketika tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas daksa, maka petugas polisi tersebut harus emmberikan akomodasi yang layak berupa pemberian layanan sementara untuk pengadu penyandang disabilitas daksa di lantai 1. Jadi akomodasi yang layak itu sifatnya sementara dan waktunya sebentar.
Hari ketiga, Yeni Rossa Damayanti, Ketua Perhimpuan Jiwa Sehat yang juga sebagai adalah trainer global untuk CRPD, diminta memberikan materi terkait Hak atas kesetraan hukum dimata disabilitas. Pasal 12 CRPD mengatur kesetaraan dimata hukum, pasal ini adalah pasal yang spesifik dibuat oleh komite CRPD, berbeda dengan pasal-pasal lain itu diadopsi dari kovenan internasional lain. Dalam Pasal 12 ini yang dimaksud kesetaraan di mata hukum mencakup kesetaraan sebagai subjek hukum dan kpasitas hukum
Yeni Rossa Damayanti kemudian menjelaskan kepada peserta terkait perbedaan antara kapasitas hukum dan subjek hukum. Kapasitas hukum adalah kesetaraan untuk mengambil keputusan hukum atau melakukan tidnakan hukum. Dengan kapasitas ini memposisikan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum.
Contoh dari tindakan hukum ini seperti membuka rekening di bank, pemberian suara dalam Pemilu, jual beliu rumah atau sepeda yang dibuktikan dengan adanya kuitansi. Tindakan hukum Itu bisa dilakukan apabila penyandang disabilitas mempunyai kapasitas hukum. Anak kecil tidak bisa membeli sepeda karena tidak memiliki pasitas hukum.
Apa yang menyebabkan seseorang atau penyandang disabilitas tidak memiliki kapasitas hukum. Penyebabnya karena stigma yang ada di lingkungan masyarakat. Ada anggapan penyandang disabilitas tidak sama atau setara untuk mengambil keputusan sendiri. “Dia dianggap tidak bisa mengambil keputusan mana yang baik atau buruk, jadi dianggap seperti anak kecul, akhirnya harus kehilangan kapasitas hukumnya”, tukas Yeni Rossa Damayanti.
Saat kehilangan kapasitas hukumnya, maka penyandang disabikltas tersebut berada dibawah pengampuan sehingga segala tindakan atau keputusan atas nama mereka dilakukan oleh walinya, seperti: membuka rekening, mengelola waris, berperkara di pengadilan, dipaksa tinggal di panti-panti sosial. Keputusannya diwakilkan oleh walinya dan penyandnag disabilitas tidak bisa menolak.
Seseorang atau penyandang disabilitas bisa dikatakan tidak cakap hukum, itu bisa karena anggapan masyarakat, tanpa melalui putusan pengadilan, atau tanpa ada pembuktian hukum. Jadi perwaliannya informal. Orang atau penyandang disabilitas ini bisa melakukan gugatan atas perwalian informal ini ke pengadilan. Kemudian ada pengampuan melalui proses pengadilan yang sudah diatur KUHPerdata, pengampuan diberikan kepada orang gila, dungu, Lansia, orang dewasa yang boros. Dengan adanya putusan pengadilan atas pengampuan maka konsekuensinya orang tersebut lepas semua haknya saat itu. Proses pengampuan dalam peradilan di Indonesia berlangsung sangat sangat cepat, rata-rata proses persidangan berlangsung selama 22 hari. Begitu pun dalam pembuktiannyajugasangat mudah, hanya cukup dengan surat. Namun surat yang disertakan tidak menjelaskan apa kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas untuk mengambil keputusansehinggatidak cakap atau butuh pengampuan, cukup dengan resep obat
Dalam banyak kasus, kekuasaan atau kewenangan yang diambil Wali itu tidak terbatas. Motif pengampuan yang dilakukan oleh wali hanpir semua didasari atas alasan ekonomi, seperti warisan. Dalam Pasal 12 Kovenan CRPD, orang yang membantu keputuisan penyandang disabilitas itu tidak permanen sifatnya, hanya pada saat atau waktu tertentu.
Alternatif selain dilakukan pengampuan, yaitu:
1. Supportive decision making. Pengambilan keputusan oleh korban dengan didukung ketika ada permasalahan. Penyandang disabilitas dijelaskan dalam pengambilan keputusan misalnya pada saat jual-beli rumah, bukan digantikan dalam pengambilan keputusan;
2. Advance directive. Pemberian surat kuasa kepada seseorang untuk menngambil keputusan atau bertindak dalam kondisi tertentu, karena untuk penyandang disabilitas mental itu kambuhan, pada situasi tertentu ketika dia relapse maka bisa ambil keputusan dari wali yang menerima kuasa;
3. Person Centered Planning. Proses penyelesaian masalah yang sedang berlangsung digunakan untuk membantu penyandang disabilitas merencanakan masa depan mereka, berfokus pada individu, dan visi orang itu tentang apa yang ingin mereka lakukan di masa depan.
Setelah paparan, para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya, diantaranya:
1. Elmi Ismau dari HWDI Nusa Tenggara Timur bertanya terkait mekanisme advokasi berdasarkan observasi penyandang disabilitas mental di daerahnya yang sulit mendapatkan hak sipil, seperti identitas Kartu Tanda Penduduk dan tidak dimasukan dalam kartu keluarga, bahkan ada kasus mereka sampai hamil, namun tidak dibawa ke ranah hukum;
2. Marlin dari HWDI Sumatera Utara, menanyakan alternativf selain pasung yang bisa dilakukan ketika penyandang disabilitas mental di panti atau rumah sakit jiwa mengalami relapse atau kambuh;
3. Erlina Marlinda dari HWDi Aceh menyatakan belum semua daerah aware terkait isu penyandang disabilitas mental, bagaimana cara pelibatan penyandang disabilitas mental dalam kehidupan berorganisasi atau kegiatan masyarakat?;
4. Ade Rita dari HWDI Majalengka menyatakan terkendala untuk mendapatkan bantuan permodalan padahal usahanya jelas, entah apa alasannya padahal yang non-disabilitas bisa mendapatkan pinjaman. “Saya single parent dan disabilitas, akhirnya saya mengajukan BPKB motor ke pegadaian, namun ditolak”, tukas Ade Rita;
5. Paini dari DPC HWDI Kota Bekasi menyatakan bahwa banyak penyandang disabilitas mental yang berkeliaran di Kota Bekasi, “kami bawa ke panti, dan sembuh, pulang ke namun, ketika pulang dikucilkan sehingga kambuh kembali. Apa yang harus dilakukan dengan penyandnag disabilitas mental tersebut?” tukas Paini.
Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, teni Rossa Damayanti menyatakan bahwa:
1. Penyandang disabilitas mental dianggap bukan warga negara atau dianggap bukan sebagai subjek hukum maka dia tidak memiliki KTP atau KK, jadi kehilangan hak sipilnya. Implikasinya tidak memiliki BPJS, tidak bisa sekolah, tidak bisa ikut dalam Pemilu. Apa yang harus dilakukan, bantu semaksimal mungkin, damping sampai depat untuk memperoleh dokumen kewarganegaraan. Terkait pertanyaan ada yang hamil, orang tersebut tidak memiliki kapasitas hukum untuk melapor. Bagaimana cara, bisa melakukan perubahan kebijakan secara nasional sampai dengan lokal atau harmonisasi hukum penyandang disabilitas tidak memiliki kapasitas hukum. Oleh karena itu, KUHPerdata harus direvisi agar sesuai dengan CRPD. Kemudian cara taktisnya dengan melibatkan atau mengundang psikolog untuk menjadi saksi ahli di pengadilan untuk argumentasi ilmu hukum di pengadilan, meskipun ini tidak ideal ketika membawa ini ke pengadilan;
2. Pertanyaan ke-2, Untuk menurunkan atau menenangkan tensi saat relapse, tu banyak cara selain pasung, ada teknik-teknik eskalasi;
3. Ketika diiperlakukan salah sebagai subjek hukum, maka kita usahakan berjejaring dengan lembaga bantuan hukum (LBH). Diupayakan agar LBH tersebut bisa berpersfektif disabilitas. Di Jakarta kita berjejaring dengan beberaopa LBH dan memberikan pelatihan CRPD sehingga mereka bisa membantu kita ketika mengalami masalah huikum;
4. Untuk pinjaman modal, kjiota bisa mnegacu pada UU 8/2016 ada kewajiban pemerintah Untuk menyediakan pinjaman, diatur dalam Pasal 56 s.d Pasal 59 UU 8/2016 terkait kewirausahaan dan permodalan yang belum dipopulerkan. Untuk mendorong ini, bisa dimasukan dalam Omnibus law Cipta Kerja, untuk memperkuat posisinya;
5. Penyandang disabilitas mental tertutup, ada 3 kemungkinan karena keluarganya melarang, kemudian takut dibongkar apa yang dilakukan oleh keluarga atas penyandng disabilitas mental, dan yang terakhir bisa juga sedang paranoid atau waham kejar, suatu perasaan ada orang yang akan menyakiti atau berbuat buruk terhadapnya; Pendekatannya harus pada keluarga, atau perlahan-lahan terhadap penyandang disabilitas mental dengan cari tahu siapa orang yang dihormatinya tersebut untuk membantu membujuk agar bisa terbuka;
6. Terkait dengan sulitnya menggadai BPKB kendaraan di Pegadaian itu karena perempuan tidak memiliki kapasitas legal, harus seizin suami;
7. Mekanime pengaduan harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas, misalnya tempatnya dekat atau ada layanan khusus telepon untuk pengaduan kasus kekerasan.
Di akhir sesi, Yusri Hayani, perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan unek-uneknya setelah terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada pelimpahan kewenangan anatara pusat, provinsi dan kabupaten atau kota, mengakibatkan penyandang disaboilitas di masyarakat itu kewenangan dinas sosial kabupaten atau kota. Sementara untuk di panti kewenangan dinas sosial provinsi. Namun dinas sosial kabupaten atau kota itu tidak siap dengan anggaran dalam APBD untuk penyandang disabilitas mental yang berkeliaran di jalan.
Terkait personalan tersebut, Yeni Rossa Damayanti menyarankan agar perwakilan DPC HWDI di kabupaten atau kota bergeriliya agar anggaran rehabilitasi sosial dianggarkan dalam APBD. Kemudian terkait kewenangan pengelolaan panti, dia menegaskan bahwa panti ini harus disiapkan seperti asrama, penghuni yang sudah stabil bisa bekerja atau keluar untuk melaksanakan aktivitas. Selain itu, dia meminta P2TP2A untuk melakukan kunjungan rutin dalam lingkup wilayahnya terkait pemantauan dan monitoring kekerasan yang mungkin terjadi.
Setelah pemaparan, para peserta dibagi dalam 6 kelompok untuk melakukan diskusi membahas 6 permasalahan yang diangkat berdasarkan kisah nyata, dan ada yang berhasil diadvokasi dan menjadi sorotan nasional bahkan internasional, yaitu kasus penolakan maskapai timur tengah menolak penumpang penyandang disabilitas,. Kemudian kasusnya tersebut berujung pada putusan maskapai tersebut didenda Rp.500 juta. Kasus-kasus lainnya, yaitu:
1. Kasus kesehatan reproduksi. Ada seorang perempuan disabilitas rungu mau pasang alat KB namun suaminya tidak bersedia menemani ke Puskesmas. Kemudian perempuan disabilitas itu pergi ke Puskesmas namun tidak mendapatkan pelayanan karena tidak ada interpreter Bahasa isyarat. Berdasarkan kasus tersebut, Kelompok 1 memberikan rekomendasi: 1) Harus ada interpreter dan alat tulis agar penyandang disabilitas rungu bisa konsultasi dengan petugas kesehatan; 2) Adanya Peraturan Daerah tentang Kesehatan Reproduksi; dan 3) Koordinasi dinas sosial provinsi dan kabupaten atau kota.
2. Kasus diskriminasi saat pembukaan rekening bank BCA untuk disabilitas netra. Rekomendasi peneyelesaian yang akomodatif adalah audiensi dengan Ombudsman, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan melibatkan media;
3. Kasus perjalanan Dwi Ariani yang ditolak maskapai tertentu dari Jakarta ke New York. Rekomendasi dari kelompok 3: 1) Perlunya membangun kesadaran di lingkungan pelaksana hak pelayanan publik; 2) Meningkatkan kapasitas pelaku pelayanan publik terkait hak penyenadang disabilitas; 3) Pertlu ada sosialisasi di lingkungan bandara terkait hak-hak penyandang disabilitas mengakses layanan transportasi udara;
4. Ada seorang ibu yang mendapatkan kekerasan karena menolak hubungan seks karena suaminya mabuk-mabukan. Rekomendasi yang diusulkan, yaitu HWDI melakukan pendampingan terhadap korban dengan bermitra dengan P2TP2A kabupaten atau kota, serta pendampingan hukum dengan LBH;
5. Kasus berkaitan dengan seorang disabilitas pisik p[erempuan tidak berhak menerima pendidikan. Usulan rekomendasi adalah Pemerintah menyediakan kartiu penyandang disabillitas dan kartu Indonesia pintar terhadap penyandang disabilitas fisik tersebut;
6. Penyandang disabilitas ditolak ikut tes CPNS karena menggunakan kursi roda, yang dianggap tidak sehat jasmani. Rekomendasi yang diajukan kelompok 6 adalah gugatan hukum.